 x
x
KARAKTER CEWE


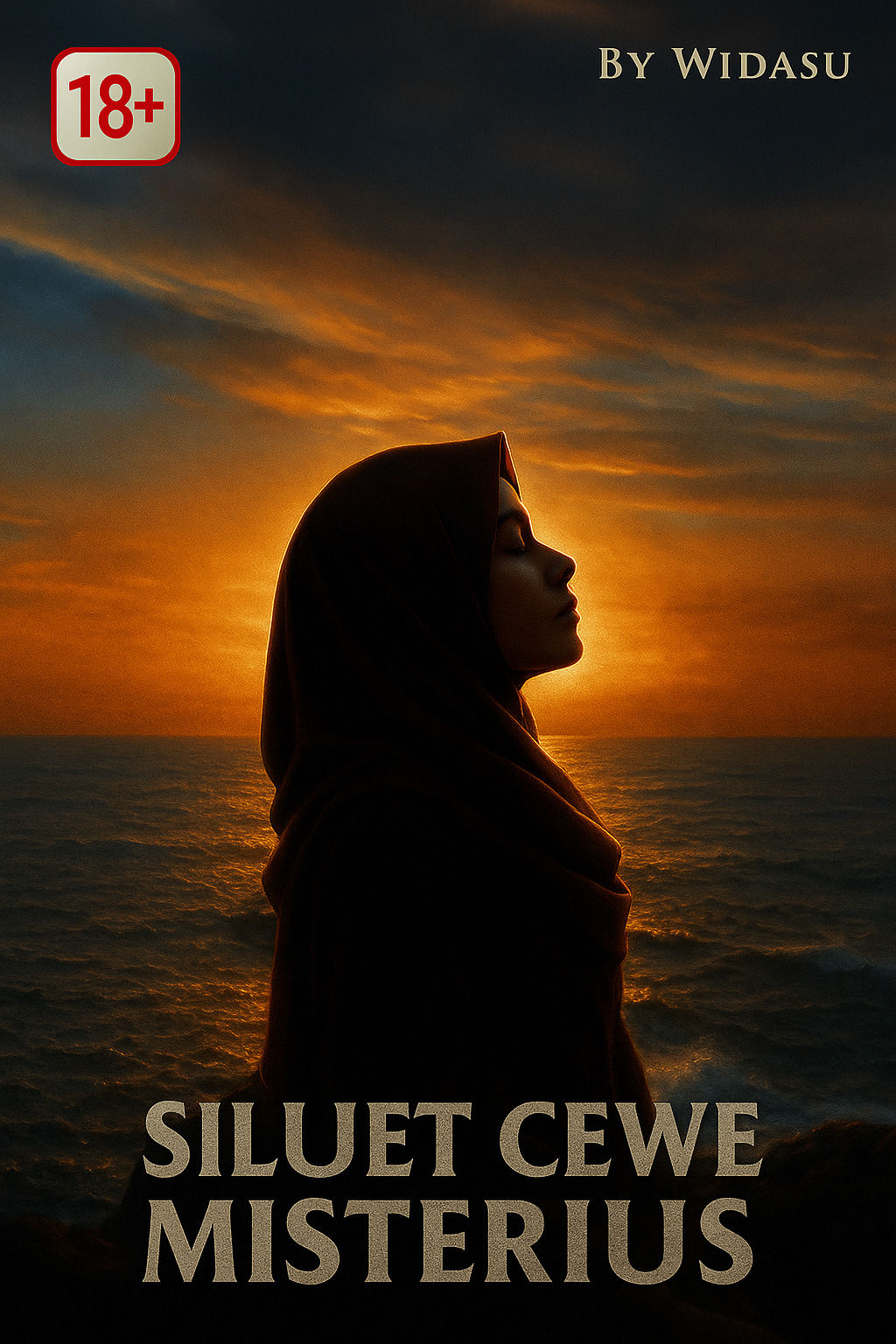

KARKTER COWO
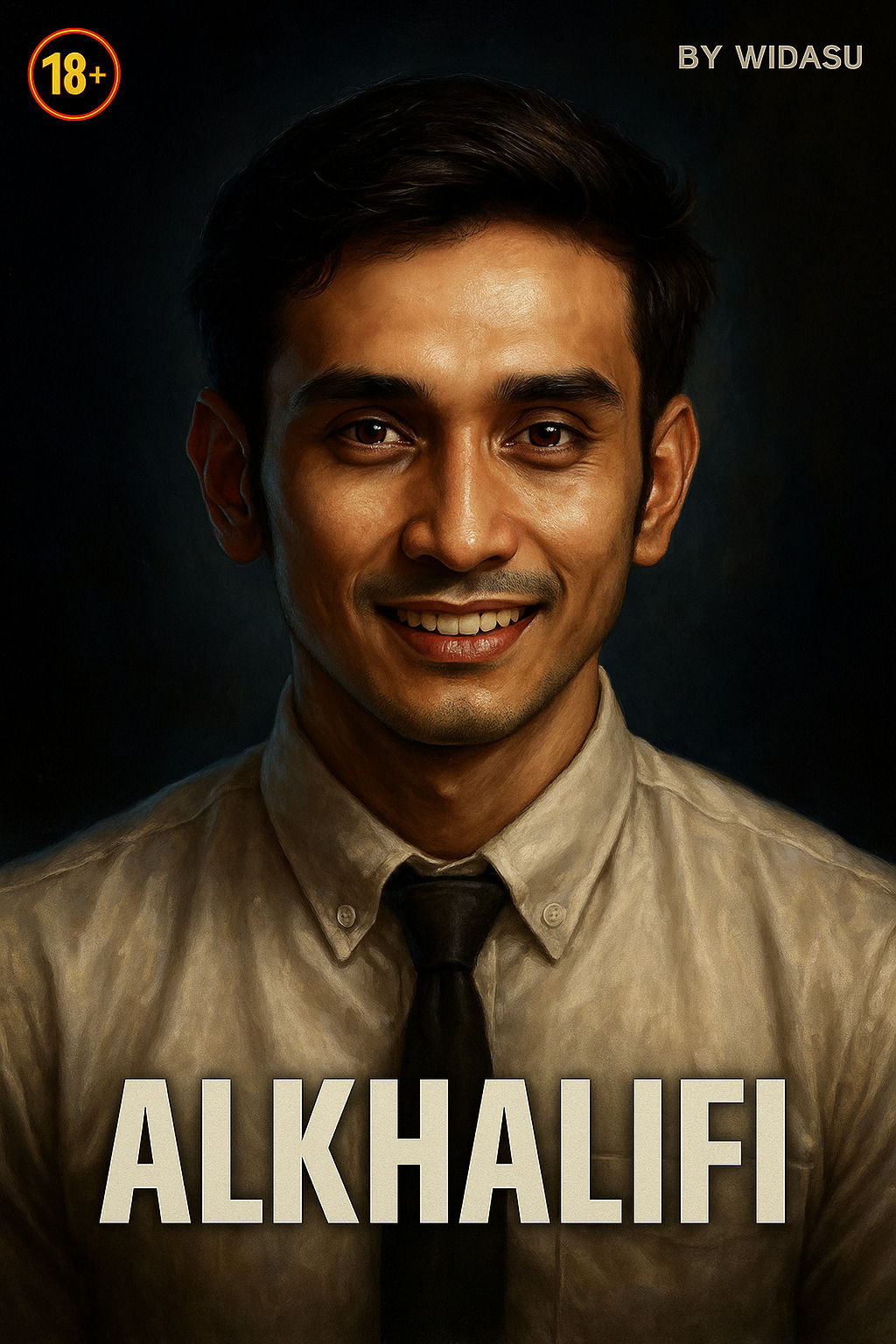

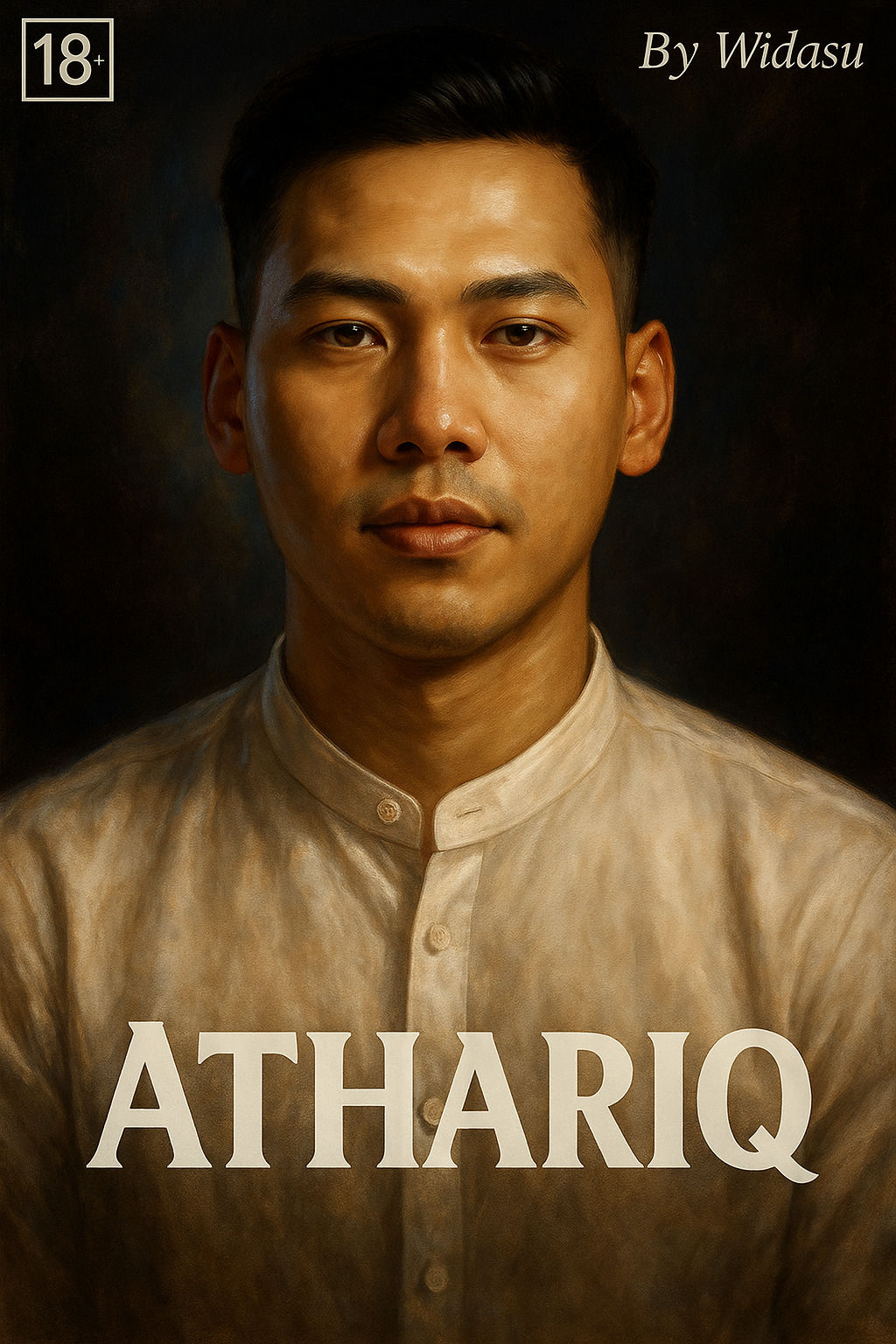




 Home
Home
 Finder (Beta)
Finder (Beta)
 Stories
Stories
 Comics
Comics
 Short pieces
Short pieces
 Contests
Contests
 Charts
Charts
 Bookshelf
Bookshelf
 Write
Write
 Society
Society
 Hub
Hub
 How to Publish
How to Publish



 will be deducted
will be deducted After each update request, the author will receive a notification!
smartphone100 → Request update
→ Request update
 Mar 11, 2025
Mar 11, 2025
 12363
12363
 1 Min Read
1 Min Read
 x
x
KARAKTER CEWE8964 copyright protection12363PENANA6xBfE2uTbR 維尼


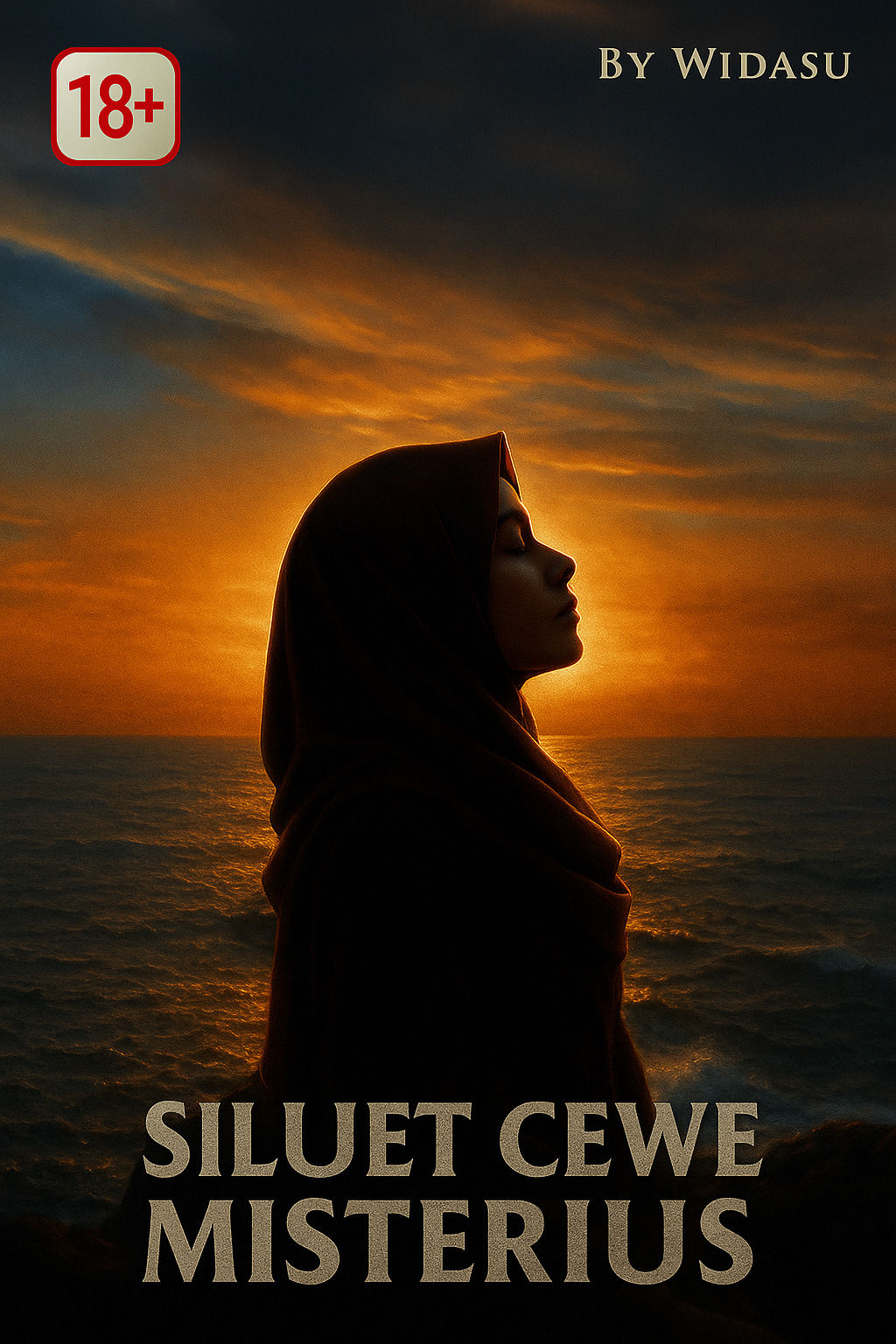
 8964 copyright protection12363PENANACPgp4ePDo9 維尼
8964 copyright protection12363PENANACPgp4ePDo9 維尼
KARKTER COWO8964 copyright protection12363PENANAzRglyPPKBy 維尼
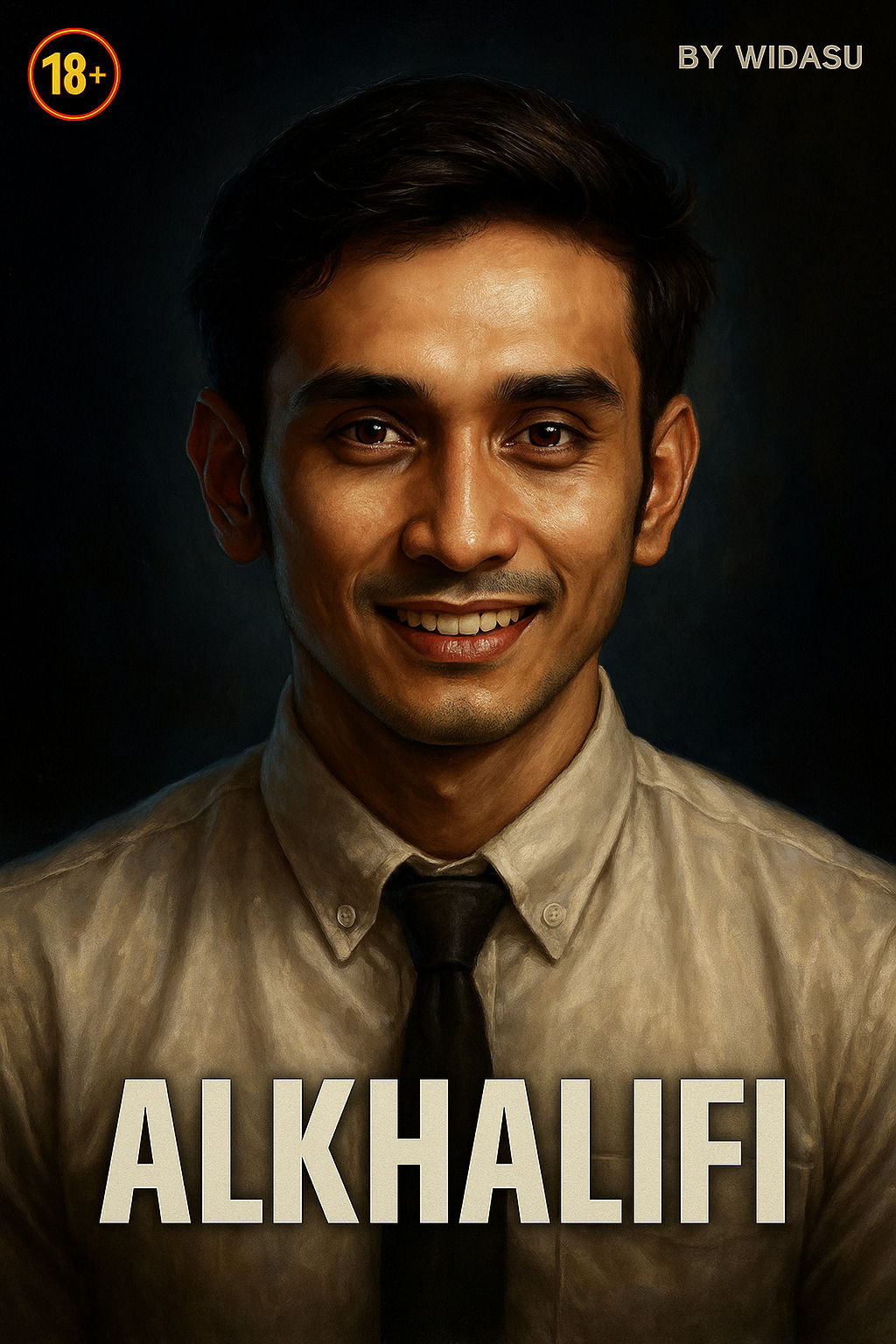

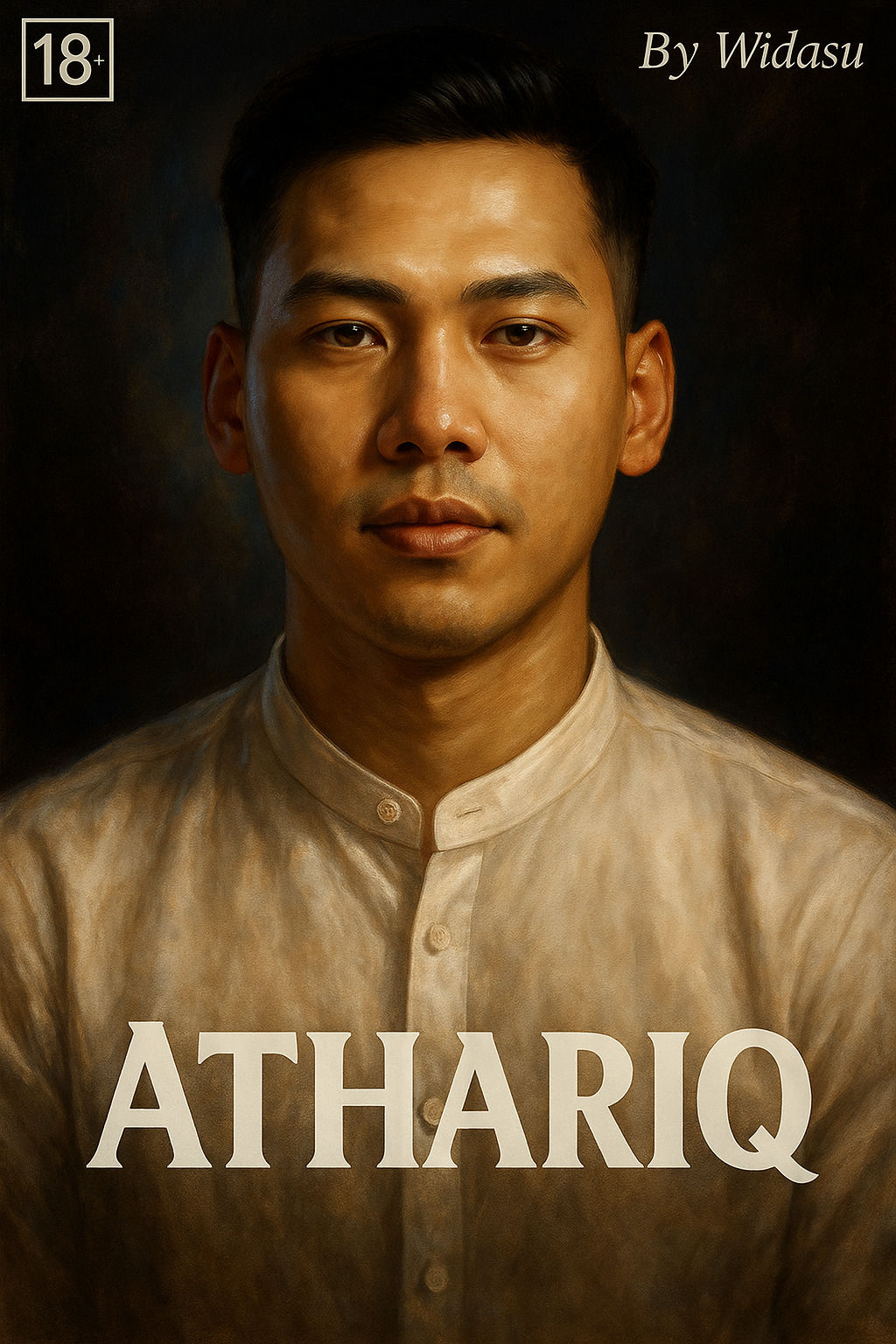



 8964 copyright protection12363PENANAAQrAmRIjAr 維尼
8964 copyright protection12363PENANAAQrAmRIjAr 維尼
216.73.216.143
ns216.73.216.143da2



 Login with Facebook
Login with Facebook

